Politikus Jadi Profesor, Tak Layak?
 |
| Ilustrasi dari kompas.com |
Belakangan, publik Indonesia heboh dengan skandal guru besar abal-abal. Banyak orang dicurigai melakukan kecurangan dalam memperoleh gelar berprestise itu. Tadinya skandal ini mencuat terkait investigasi terhadap sebelas dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, yang mendapat gelar profesor lewat jalan pintas.
Lalu menyerempet ke para politikus yang mendapat gelar profesor. Sorotan tertuju kepada Sufmi Dasco Ahmad, politisi Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI yang baru dinobatkan jadi profesor dua tahun lalu. Juga, menyasar Bambang Soesatyo, politisi Golkar dan Ketua MPR RI, yang sedang mengajukan gelar profesor ke Kemendikbud Ristek.
Dasco dan Bambang, bukan pencipta tradisi ini. Banyak politikus lain yang lebih duluan dianugerahi gelar profesor. Sebutkan saja beberapa yang paling populer, Megawati Soekarnoputri (PDIP), Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Siti Nurbaya Bakar (NasDem), dan Fahmi Idris (Golkar).
Pakar atau Karir?
Perdebatan layak atau tak layak politikus jadi profesor berpunca dari keberbedaan sudut pandang. Sebagian orang melihat profesor sebagai karir akademik di lingkungan perguruan tinggi. Perspektif lain melihatnya sebagai kualifikasi intelektual atau kepakaran pada bidang keilmuan tertentu.
Regulasi di Indonesia mengakomodir keduanya. Guru besar sebagai gelar karir hanya diberikan kepada akademisi yang aktif mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat mengikuti cara-cara yang dipikirkan oleh orang-orang di perguruan tinggi.
Sisi lain, terdapat gelar profesor kehormatan yang diberikan kepada kalangan non-akademisi berdasarkan penilaian capaian keilmuan atau kepakaran di bidang tertentu. Selain karena dinilai sangat pakar, profesor kehormatan diberikan kepada kalangan yang tidak berkarir di dunia akademik, tetapi menyempatkan diri mengajar di perguruan tinggi. Hal ini diatur dalam Permendikbud Ristek 38/2021.
Karenanya, orang-orang yang masih meributkan pemberian gelar profesor kepada politikus ada dua kemungkinan. Pertama, mengira profesor hanya gelar karir akademik, atau kedua, meragukan kepakaran atau kualifikasi keilmuan para politikus dalam bidang spesifik.
Memang, capaian jenjang karir lebih mudah dinilai dan diperiksa berdasarkan syarat-syarat administrasi tertentu. Namun, tidak cukup mudah memberi penilaian dan mengukur kualifikasi keilmuan para politisi. Bisakah kepakaran bidang keilmuan hanya dinilai dari publikasi di jurnal internasional bereputasi?
Dari era Yunani kuno, para filsuf sudah menyadari bahwa ilmu itu berdimensi ganda, teoritis dan praksis. Sederhananya, penguasaan ilmu atau kepakaran tidak dapat dibatasi penilaiannya cuma dari sisi kemampuan menjelaskan realitas. Apalagi dibatasi pada tingkat kemampuan menjelaskan realitas dengan tulisan. Kepakaran juga harus dinilai dari penguasaan sisi praksis ilmu itu. Mencakup penguasaan tindakan yang tepat (praksiologi) dan penguasaan teknis yang akurat (teknologi).
Itu sebabnya, dunia keilmuan harus mengakui kualifikasi kepakaran para praktisi, bahkan jika mereka tidak lihai dalam menjelaskan dan menuliskan ilmunya menggunakan kaidah-kaidah akademik yang baku dan kaku.
Seorang seniman tradisional yang menguasai seni tutur sejenis Hikayat atau Wayang tentu lebih pakar di bidangnya ketimbang akademisi yang mampu menjelaskan seni tutur dalam ribuan halaman buku tanpa keterampilan mempraktekkan seni tutur itu.
Para pengusaha sekelas Yusuf Kalla, Aburizal Bakri, Dedi Panigoro, dan Surya Paloh tak bisa dianggap kurang pakar dalam bisnis dibandingkan dosen-dosen manajemen bisnis di perguruan tinggi. Mungkin para dosen mampu menulis di jurnal-jurnal bereputasi Scopus, tetapi mereka tak pernah berhasil membangun satu perusahaan pun sebagai model nyata.
Kepakaran yang teruji adalah penguasaan praksis. Masih bisa ditolerir jika praktisi kekurangan kemampuan menjelaskan keberhasilan mereka dalam standar kaidah-kaidah tertentu. Justru, karaguan lebih layak dilayangkan pada para akademisi yang mengukur kepakaran mereka dari jumlah bacaan dan tulisan semata. Bacaan dan tulisan boleh jadi ukuran pengetahuan, bukan ukuran kepakaran.
Dalam bidang-bidang keilmuan ekonomi dan politik, kepakaran menuntut lebih banyak penguasaan sisi praktis ketimbang teoritis. Saya berpikir demikian, ketika filsuf sosial abad 20, Ludwig von Mises mendalilkan cabang-cabang keilmuan sosial yang mengkaji tindakan manusia, seperti ekonomi dan politik, harusnya dibawah kategori disiplin ilmu praksiologi. Dimaksudkan bahwa seorang pakar dalam bidang-bidang ini adalah orang yang paling menguasai terapan-terapan lapangan mestinya.
Teruji di dunia nyata. Bukan teruji di dunia diskursus dalam perdebatan di jurnal-jurnal ilmiah yang diatur untuk kepentingan bisnis industri dunia akademik belaka. Seringkali terputus relevansinya dengan kehidupan harian jutaan rakyat umum.
Tentu, pemilahan aspek teoritis dan praktis pada faktualnya tidak pernah benar-benar bisa dipisahkan secara dualistik. Setiap tindakan yang dipilih dalam dunia politik atau ekonomi, selalu melalui sebuah proses penalaran (reasoning) di belakang tindakan itu. Penalaran-penalaran itu lebih teoritis, karena menyangkut cara baca seseorang menilai kenyataan dalam ruang-waktu tempat kehidupan sedang berjalan. Ini berlaku universal pada semua kelas sosial masyarakat.
Persoalannya dimulai ketika penalaran-penalaran itu dianggap sah dan sahih jika dituliskan dalam standar-standar komunitas akademik. Sejak itu pula, kepakaran tidak lagi diukur dari penguasaan sisi praksis ilmu. Dipaksa ukur dari kemampuan mengkomunikasikannya dengan komunitas-komunitas ilmiah antarabangsa.
Politikus itu Teruji
Dasco, SBY, Megawati dan seterusnya dalam daftar politikus Indonesia yang sudah memperoleh gelar profesor layak diragukan kepakaran mereka. Jika kepakaran itu dinilai dan diukur secara salah. Bila kepakaran menuntut kemampuan menulis sendiri artikel-artikel berbobot menggunakan kaidah-kaidah ilmiah berstandar jurnal-jurnal internasional bereputasi.
Ilmu politik sebagai bagian dari praksiologi mestinya menolak premis-premis semacam itu. Para politikus itu bertahun-tahun bergelut dan memproduksi kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat umum. Mereka teruji mengatur keamanan publik, penyelesaian konflik-konflik kepentingan, distribusi kesejahteraan umum, dan perkara-perkara lainnya dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Sangat aneh, jika para akademisi mengira dosen-dosen ilmu politik dan ilmu hukum lebih pakar dari para politikus di jabatan publik. Para dosen padahal hanya bekerja melipatgandakan bacaan dan tulisan. Mengutip sana sini dari hasil-hasil penelitian orang lain dan mengkomunikasikannya dalam sebuah cara yang disebut diskursus akademik.
Politikus dengan pengalaman panjang mereka di jabatan publik lebih layak bergelar profesor dari tinjauan kepakaran. Para dosen lebih layak bergelar profesor dari sisi karir akademik. Keduanya sah, benar, dan patut.
Tulisan Affan Ramli, Tayang di Kompas dan KemenPanRB

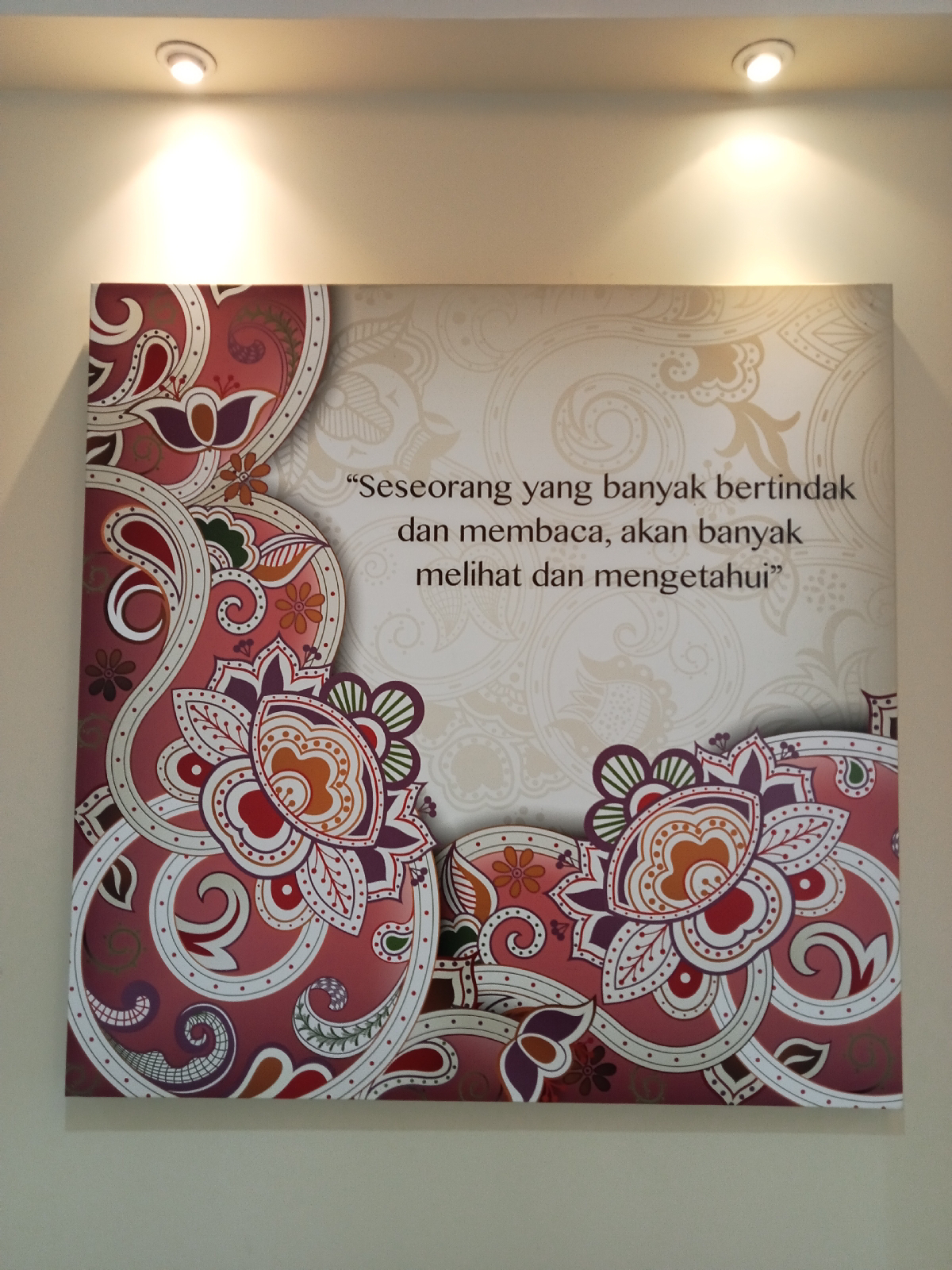
Comments
Post a Comment